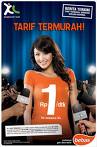HASIL UN 2013/2014
Pengumuman kelulusan Ujian Nasional SMAN 6 Semarang tanggal 20 Mei 2014.
Halaman ini dipersiapkan untuk pengumuman kelulusan siswa SMAN 6 Semarang tahun ajaran 20013/2014. bagi anda siswa atau orangtua atau siapa saja warga sekolah yang ingin tahu tentang , pada saatnya nanti halaman ini akan berganti dengan pengumuman kelulusan
semua ada disini
Jumat, 19 September 2008
Senin, 08 September 2008
Sejarah nama Indonesia
Sejarah nama Indonesia
Untuk artikel tentang nama orang-orang Indonesia, lihat Nama Indonesia
Pada zaman purba, kepulauan Indonesia disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.
Bangsa Arab menyebut wilayah yang kemudian menjadi IndonesiaJaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan adalah benzoe, berasal dari bahasa Arab luban jawi (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatra. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "Jawa" oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatra), Sholibis (Sulawesi), Sundah (Sunda), semua pulau itu dikenal sebagai kulluh Jawi (semuanya Jawa).
Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah "Hindia". Semenanjung Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang". Sedangkan tanah air memperoleh nama "Kepulauan Hindia" (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau "Hindia Timur" (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).
Pada jaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).
Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.
Nusantara
Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memperkenalkan suatu nama untuk Indonesia yang tidak mengandung unsur kata "India". Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.
Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis "Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa" (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat).
Oleh Dr. Setiabudi kata nusantara zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu "nusa di antara dua benua dan dua samudra", sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda.
Sampai hari ini istilah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan Indonesia.
Nama Indonesia
Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.
Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis:
"... the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians".
Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (Srilanka) dan Maldives (Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.
Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah "Indian Archipelago" terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.
Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan:
"Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago".
Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.
Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie tahun 1918. Padahal Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.
Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.
Nama indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan indonesiër (orang Indonesia).
Politik
Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu.
Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.
Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,:
"Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia Belanda". Juga tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."
Di Indonesia Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama "Indonesia". Akhirnya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.
Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar nama "Indonesia" diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Tetapi Belanda menolak mosi ini.
Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia Belanda". Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Republik Indonesia.
Nama Indonesia dalam berbagai bahasa
• Indonesia (Bahasa Finlandia, Indonesia, Italia, Melayu, Romans, Spanyol)
• Indónesía (Eslandia)
• Indonésia (Portugis)
• Indonesja (Malta)
• Indonésie (Ceko, Perancis)
• Indonesië (Afrikan, Belanda)
• Indonesien (Jerman, Swedia)
• Indonezia (Rumania)
• Indonézia (Hongaria)
• Indonezja (Polandia)
• Indonezija (Kroasia, Lithuania, Slovenia)
• Indonēzija (Latvia)
• Indonezio (Esperanto)
• Endonezya (Turki)
• Indonesiana (Pig Latin)
• Indoneesia (Estonia)
• Indoneesiä (Võro)
• Indoneziya - Индонезия (Bulgaria, Rusia)
• Indoneshia - インドネシア (Jepang)
• Indonisía - Ινδονησία (Yunani)
• Indonashia - انڈونیشیا - (Urdu)
• Yìndùnìxīyà - 印度尼西亞 / 印尼 - baca: Intunisiya(Tionghoa)
Pranala luar
• (id) Asal Usul Nama Indonesia
• (id) Asal-usul Kata Indonesia
• (id) Pusatbahasa: Nama Indonesia Read More...
Untuk artikel tentang nama orang-orang Indonesia, lihat Nama Indonesia
Pada zaman purba, kepulauan Indonesia disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.
Bangsa Arab menyebut wilayah yang kemudian menjadi IndonesiaJaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan adalah benzoe, berasal dari bahasa Arab luban jawi (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatra. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "Jawa" oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatra), Sholibis (Sulawesi), Sundah (Sunda), semua pulau itu dikenal sebagai kulluh Jawi (semuanya Jawa).
Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah "Hindia". Semenanjung Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang". Sedangkan tanah air memperoleh nama "Kepulauan Hindia" (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau "Hindia Timur" (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).
Pada jaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).
Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.
Nusantara
Pada tahun 1920-an, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (1879-1950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memperkenalkan suatu nama untuk Indonesia yang tidak mengandung unsur kata "India". Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.
Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis "Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa" (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat).
Oleh Dr. Setiabudi kata nusantara zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu "nusa di antara dua benua dan dua samudra", sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda.
Sampai hari ini istilah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan Indonesia.
Nama Indonesia
Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.
Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis:
"... the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians".
Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (Srilanka) dan Maldives (Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.
Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah "Indian Archipelago" terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.
Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan:
"Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago".
Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.
Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie tahun 1918. Padahal Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.
Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.
Nama indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan indonesiër (orang Indonesia).
Politik
Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama "Indonesia" akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu.
Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.
Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,:
"Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia Belanda". Juga tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."
Di Indonesia Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama "Indonesia". Akhirnya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.
Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar nama "Indonesia" diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Tetapi Belanda menolak mosi ini.
Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia Belanda". Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Republik Indonesia.
Nama Indonesia dalam berbagai bahasa
• Indonesia (Bahasa Finlandia, Indonesia, Italia, Melayu, Romans, Spanyol)
• Indónesía (Eslandia)
• Indonésia (Portugis)
• Indonesja (Malta)
• Indonésie (Ceko, Perancis)
• Indonesië (Afrikan, Belanda)
• Indonesien (Jerman, Swedia)
• Indonezia (Rumania)
• Indonézia (Hongaria)
• Indonezja (Polandia)
• Indonezija (Kroasia, Lithuania, Slovenia)
• Indonēzija (Latvia)
• Indonezio (Esperanto)
• Endonezya (Turki)
• Indonesiana (Pig Latin)
• Indoneesia (Estonia)
• Indoneesiä (Võro)
• Indoneziya - Индонезия (Bulgaria, Rusia)
• Indoneshia - インドネシア (Jepang)
• Indonisía - Ινδονησία (Yunani)
• Indonashia - انڈونیشیا - (Urdu)
• Yìndùnìxīyà - 印度尼西亞 / 印尼 - baca: Intunisiya(Tionghoa)
Pranala luar
• (id) Asal Usul Nama Indonesia
• (id) Asal-usul Kata Indonesia
• (id) Pusatbahasa: Nama Indonesia Read More...
Selasa, 19 Agustus 2008
ARTIS DALAM PANGGUNG POLITIK ?
Pengertian Partisipasi Politik
Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).
Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.
Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :
a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
2. Konsep Partisipasi Politik
Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan Post Behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.
Dalam ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ? siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik.
Sejak musim pemilu 2004 lalu, trend partai politik di Indonesia mulai banyak diwarnai dengan kehadiran artis-artis yang secara langsung terlibat ke dalam kegiatan politik. Jika sebelumnya mereka lebih banyak dipilih atau dipromosikan ke lembaga legislatif, kini kehadiran artis sudah masuk ke dalam level pemerintahan. Sejauh ini mereka masih ditempatkan sebagai wakil seperti yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat. Kini sudah mulai ramai pula para kandidat pilkada di beberapa daerah menggunakan artis untuk mendampinginya pada kampanye dan pilkada. Pandangan masyarakat umum tentu bisa memahami jika kehadiran artis dalam panggung politik sejauh ini hanyalah dimanfaatkan popularitasnya. Sejauh manakah kontribusi mereka dalam percaturan politik di tanah air? Sejauh mana pula partai politik memanfaatkannya?
Memasuki masa reformasi, peta politik di tanah air mulai banyak mengalami perubahan. Sudah tidak ada lagi dominasi tiga partai seperti sebelumnya. Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik memberikan kebebasan kepada siapapun warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat Bab II, Pasal 2, UU No 31/2002)
Tidak ada batasan atas jumlah partai politik yang dapat akan didaftarkan menjadi peserta pemilu. Undang-Undang No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik membuka peluang di antara partai politik untuk bersaing mendapatkan dukungan dari pemilih-pemilihnya.
Peluang untuk mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih sangat ditentukan oleh popularitas dari partai politik. Ada cukup banyak aspek yang mendasari terbentuknya popularitas partai politik. Mulai nama besar pendiri, kontribusinya secara langsung kepada pemilih-pemilihnya, peran secara politik terhadap masyarakat baik pemilih maupun bukan pemilihnya, hingga orang-orang yang menggerakkannya. Kunci untuk memenangkan popularitas ini terletak dari kemampuan partai politik dalam memahami cara berpikir calon-calon pemilihnya, bukan didasarkan pada kemampuan untuk memahami apa yang diinginkan oleh calon pemilihnya.
Sejak Pemilu 2004 lalu, nampaknya cara berpikir masyarakat Indonesia masih lebih banyak yang melihat atau menilai politik berdasarkan atribut fisik. Ketika Pilpres 2004 lalu, tidak banyak yang mengenal siapa sesungguhnya SBY yang akhirnya terpilih menjadi Presiden RI Ke-6. Masyarakat hanya mengetahui beliau ini mengundurkan diri karena merasa dikucilkan dalam kabinet Megawati ketika itu. Partai Demokrat ketika itu menjual simpati dan rasa iba sebagai komoditas politik, dan berhasil. Hampir tidak berbeda dengan kebanyakan tayangan sinetron yang lebih banyak menjual simpati dan rasa iba, bukan kualitasnya. Tim sukses SBY bersama Partai Demokrat ketika itu berhasil memahami cara berpikir masyarakat atau calon-calon pemilihnya.
Melihat cara berpikir masyarakat yang lebih mendasarkan penilaiannya pada aspek fisik, maka terbuka peluang untuk mendongkrak popularitas partai dengan cara menggandeng tokoh-tokoh yang populer. Sejauh ini, tokoh masyarakat yang dianggap populer selain presiden adalah mereka yang berada di kalangan artis. Mereka ini lebih banyak terlihat di acara televisi seperti sinetron dan infotainment yang umumnya paling digemari oleh sebagian besar masyarakat. Pihak atau kalangan artis sendiri juga cukup banyak Read More...
Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).
Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.
Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :
a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
2. Konsep Partisipasi Politik
Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan Post Behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.
Dalam ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ? siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik.
Sejak musim pemilu 2004 lalu, trend partai politik di Indonesia mulai banyak diwarnai dengan kehadiran artis-artis yang secara langsung terlibat ke dalam kegiatan politik. Jika sebelumnya mereka lebih banyak dipilih atau dipromosikan ke lembaga legislatif, kini kehadiran artis sudah masuk ke dalam level pemerintahan. Sejauh ini mereka masih ditempatkan sebagai wakil seperti yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat. Kini sudah mulai ramai pula para kandidat pilkada di beberapa daerah menggunakan artis untuk mendampinginya pada kampanye dan pilkada. Pandangan masyarakat umum tentu bisa memahami jika kehadiran artis dalam panggung politik sejauh ini hanyalah dimanfaatkan popularitasnya. Sejauh manakah kontribusi mereka dalam percaturan politik di tanah air? Sejauh mana pula partai politik memanfaatkannya?
Memasuki masa reformasi, peta politik di tanah air mulai banyak mengalami perubahan. Sudah tidak ada lagi dominasi tiga partai seperti sebelumnya. Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik memberikan kebebasan kepada siapapun warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku (lihat Bab II, Pasal 2, UU No 31/2002)
Tidak ada batasan atas jumlah partai politik yang dapat akan didaftarkan menjadi peserta pemilu. Undang-Undang No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik membuka peluang di antara partai politik untuk bersaing mendapatkan dukungan dari pemilih-pemilihnya.
Peluang untuk mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih sangat ditentukan oleh popularitas dari partai politik. Ada cukup banyak aspek yang mendasari terbentuknya popularitas partai politik. Mulai nama besar pendiri, kontribusinya secara langsung kepada pemilih-pemilihnya, peran secara politik terhadap masyarakat baik pemilih maupun bukan pemilihnya, hingga orang-orang yang menggerakkannya. Kunci untuk memenangkan popularitas ini terletak dari kemampuan partai politik dalam memahami cara berpikir calon-calon pemilihnya, bukan didasarkan pada kemampuan untuk memahami apa yang diinginkan oleh calon pemilihnya.
Sejak Pemilu 2004 lalu, nampaknya cara berpikir masyarakat Indonesia masih lebih banyak yang melihat atau menilai politik berdasarkan atribut fisik. Ketika Pilpres 2004 lalu, tidak banyak yang mengenal siapa sesungguhnya SBY yang akhirnya terpilih menjadi Presiden RI Ke-6. Masyarakat hanya mengetahui beliau ini mengundurkan diri karena merasa dikucilkan dalam kabinet Megawati ketika itu. Partai Demokrat ketika itu menjual simpati dan rasa iba sebagai komoditas politik, dan berhasil. Hampir tidak berbeda dengan kebanyakan tayangan sinetron yang lebih banyak menjual simpati dan rasa iba, bukan kualitasnya. Tim sukses SBY bersama Partai Demokrat ketika itu berhasil memahami cara berpikir masyarakat atau calon-calon pemilihnya.
Melihat cara berpikir masyarakat yang lebih mendasarkan penilaiannya pada aspek fisik, maka terbuka peluang untuk mendongkrak popularitas partai dengan cara menggandeng tokoh-tokoh yang populer. Sejauh ini, tokoh masyarakat yang dianggap populer selain presiden adalah mereka yang berada di kalangan artis. Mereka ini lebih banyak terlihat di acara televisi seperti sinetron dan infotainment yang umumnya paling digemari oleh sebagian besar masyarakat. Pihak atau kalangan artis sendiri juga cukup banyak Read More...
Senin, 11 Agustus 2008
kreativitas dalam belajar: HAKIKAT BANGSA DAN NKRI
HAKIKAT BANGSA DAN NKRI............untuk selanjutnya klik disini:
"HAKIKAT BANGSA DAN UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUKNYA
A. Pengertian Negara
Menurut George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu; sedangkan Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
B. Unsur-unsur terbentuknya bangsa
1. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu.
2. Berada dalam suatu wilayah tertentu .
3. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya
sendiri .
4. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita .
5. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat
dibedakan dengan bangsa lainnya." Read More...
"HAKIKAT BANGSA DAN UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUKNYA
A. Pengertian Negara
Menurut George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu; sedangkan Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
B. Unsur-unsur terbentuknya bangsa
1. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu.
2. Berada dalam suatu wilayah tertentu .
3. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya
sendiri .
4. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita .
5. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat
dibedakan dengan bangsa lainnya." Read More...
HAKIKAT BANGSA DAN NKRI
HAKIKAT BANGSA DAN UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUKNYA
A. Pengertian Negara
Menurut George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu; sedangkan Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
B. Unsur-unsur terbentuknya bangsa
1. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu.
2. Berada dalam suatu wilayah tertentu .
3. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya
sendiri .
4. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita .
5. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat
dibedakan dengan bangsa lainnya.
Unsur-unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Unsur konstitutif ( keberadaannya mutlak harus ada ), terdiri atas :
* Rakyat
* Wilayah
* Pemerintahan yang berdaulat
2. Unsur deklaratif ( bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka memenuhi
unsur tata aturan pergaulan internasional ), yaitu :
* Pengakuan dari negara lain, yang terdiri dari :
a. Pengakuan De Facto, yaitu pengakuan menurut kenyataan yang ada (sesuai
dengan fakta). Misalnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan
kemerdekaannya.
b. Pengakuan De Jure, yaitu pengakuan secara resmi menurut hukum. Misalnya,
Indonesia diakui secara resmi oleh Mesir pada tanggal 10 Juni 1947.
Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lauterpacht, unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah sebagai berikut :
1. Rakyat yang bersatu.
2. Daerah atau wilayah.
3 Pemerintah yang berdaulat.
4. Pengakuan dari negara lain.
C. Sifat hakikat suatu negara
Sifat dan hakikat negara menurut Prof . Miriam Budiardjo mencakup hal-hal
sebagai berikut :
1. Sifat Memaksa
Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuatan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Dengan sifat memaksa ini diharapkan semua peraturan perundangan yang berlaku ditaati supaya keamanan dan ketertiban negara tercapai. Bentuk paksaan yang dapat dilihat dalam suatu negara adalah adanya Undang-Undang perpajakan yang memaksa setiap warga negara untuk membayar pajak, bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman.
2. Sifat Monopoli
Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Misalnya negara dapat mengatakan bahwa aliran kepercayaan atau partai politik tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara.
3. Sifat Mencakup Semua ( All - embracing )
Semua peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Hal itu perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.
BENTUK-BENTUK KENEGARAAN
Ada beberapa bentuk-bentuk kenegaraan, antara lain adalah :
Koloni
Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain . Dalam negara koloni,urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih tergantung pada negara yang menjajahnya.
Contoh : Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama lebih kurang 350 tahun.
Trustee ( Perwalian )
Trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang .
Contoh : Papua New Guinea bekas jajahan Inggris berada di bawah naungan PBB sampai
dengan tahun 1975.
Mandat
Mandat adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa - Bangsa ( LBB ).
Contoh : Negara Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat Perancis
Dominion
Dominion adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai raja/ratunya (lambang persatuan).
Negara-negara dominion tergabung dalam The British Commonwealth of Nations ( Negara-negara Persemakmuran ). Negara-negara dominion mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan penuh dalam mengurus praktek-praktek ke dalam maupun ke luar.
Contoh : Negara Kanada, Australia , Selandia Baru , dan Afrika Selatan .
Uni
Uni adalah gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama.
Uni dapat dibedakan tiga macam yaitu :
a). Uni Personil ( Personele Unie ) yaitu dua negara yang kebetulan mempunyai raja yang
sama sebagai kepala negara . Sementara itu, segala urusan dalam dan luar negeri diurus
oleh masing-masing negara.
Contoh : * Benelux ( Belgia , Nederland , dan Luxemburg ) yang tergabung dalam Uni
Personil tahun 1839 - 1890
* Inggris - Scotland tahun 1603 - 1707
b). Uni Riil ( Reele Unie ) yaitu dua negara yang berdasarkan suatu traktat mengadakan
ikatan yang dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat perlengkapan uni guna
mengatur kepentingan bersama . Kepentingan bersama itu umumnya berupa persoalan-
persoalan yang menyangkut politik luar negeri.
Contoh : * Uni Austria - Hongaria tahun 1867 - 1919
* Uni Swedia - Norwegia tahun 1815 - 1905
c). Uni Zui Generalis yaitu gabungan negara yang mempunyai alat kelengkapan bersama
untuk mengurus kepentingan hubungan luar negeri , setelah adanya kesepakatan lewat
perjanjian.
Contoh : Uni Indonesia - Belanda tahun 1949 - 1950
TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA
A. Tujuan Negara
Negara dapat dipandang sebagai persekutuan manusia yang hidup dan bekerjasama
untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Pada umumnya tujuan akhir setiap negara adalah
menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Oleh karena itu bagi suatu negara, tujuan merupakan hal yang sangat penting sebab tujuan
akan sangat menentukan bagaimana suatu negara mengatur, menyusun, dan menyelenggara-
kan pemerintahannya guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
Sejalan dengan banyaknya corak tujuan yang hendak diwujudkan oleh suatu negara,
banyak pemikir negara dan ahli hukum yang membahas dan mengemukakannya dalam
suatu teori. Beberapa di antaranya adalah :
Nama Tokoh
Tujuan Negara
a. Lord Shang Yang
Mencapai kekuasaan negara dengan cara rakyat dan negara harus berbanding terbalik. Bila negara ingin kuat dan sejahtera, maka rakyat harus lemah, miskin, dan bodoh.
b. Niccolo Machiavelli
Mencapai kekuasaan negara dengan cara menitik-beratkan pada sifat pribadi raja, agar dapat cerdik seperti kancil dan menakut-nakuti rakyatnya seperti singa .
c. Dante Alleghieri
Mencapai perdamaian dunia dengan cara membentuk satu negara di bawah satu imperium dunia ( raja atau kaisar ).
d. Immanuel Kant
Menjamin hak dan kebebasan warga negara .
e. Kranenburg
Mengupayakan kesejahteraan warga negaranya
(Welfare State)
Tujuan Negara Republik Indonesia terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
IV, yaitu :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial .
B. Fungsi Negara
Fungsi Negara perlu ditetapkan sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi
tercapainya tujuan Negara.
Tokoh-tokoh yang pendapatnya tentang fungsi negara diterapkan oleh negara-negara di
dunia adalah :
* John Locke
John Locke membedakan fungsi negara menjadi tiga yaitu :
1. Fungsi Legislatif : membuat Undang-Undang.
2. Fungsi Eksekutif : melaksanakan Undang-Undang , termasuk mengadili pelanggar
Undang - Undang.
3. Fungsi Federatif : mengurusi urusan luar negeri dan perang serta damai
( Hubungan dengan negara lain ).
* Montesquieu
Montesquieu membedakan fungsi negara atas tiga tugas pokok yaitu :
1. Fungsi Legislatif : membuat Undang-Undang.
2. Fungsi Eksekutif : melaksanakan Undang-Undang , termasuk mengadakan
hubungan luar negeri, membuat perjanjian dengan negara lain,
dll.
3. Fungsi Yudikatif : mengawasi agar semua peraturan ditaati ( fungsi mengadili
terhadap pelanggar Undang-Undang ).
PATRIOTISME DAN NASIONALISME
Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang sudi mengorbankan
segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.
Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri .
Nasionalisme menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Nasionalisme dalam arti sempit
Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya
yang sangat tinggi dan berlebihan, namun terhadap bangsa lain memandang rendah. Hal ini sering disamakan dengan Jingoisme atau Chauvinisme.
2. Nasionalisme dalam arti luas
Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan
bangsanya yang tinggi, tetapi terhadap bangsa lain tidak memandang rendah.
Read More...
A. Pengertian Negara
Menurut George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu; sedangkan Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
B. Unsur-unsur terbentuknya bangsa
1. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu.
2. Berada dalam suatu wilayah tertentu .
3. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya
sendiri .
4. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita .
5. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat
dibedakan dengan bangsa lainnya.
Unsur-unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Unsur konstitutif ( keberadaannya mutlak harus ada ), terdiri atas :
* Rakyat
* Wilayah
* Pemerintahan yang berdaulat
2. Unsur deklaratif ( bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka memenuhi
unsur tata aturan pergaulan internasional ), yaitu :
* Pengakuan dari negara lain, yang terdiri dari :
a. Pengakuan De Facto, yaitu pengakuan menurut kenyataan yang ada (sesuai
dengan fakta). Misalnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan
kemerdekaannya.
b. Pengakuan De Jure, yaitu pengakuan secara resmi menurut hukum. Misalnya,
Indonesia diakui secara resmi oleh Mesir pada tanggal 10 Juni 1947.
Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lauterpacht, unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah sebagai berikut :
1. Rakyat yang bersatu.
2. Daerah atau wilayah.
3 Pemerintah yang berdaulat.
4. Pengakuan dari negara lain.
C. Sifat hakikat suatu negara
Sifat dan hakikat negara menurut Prof . Miriam Budiardjo mencakup hal-hal
sebagai berikut :
1. Sifat Memaksa
Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuatan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Dengan sifat memaksa ini diharapkan semua peraturan perundangan yang berlaku ditaati supaya keamanan dan ketertiban negara tercapai. Bentuk paksaan yang dapat dilihat dalam suatu negara adalah adanya Undang-Undang perpajakan yang memaksa setiap warga negara untuk membayar pajak, bila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman.
2. Sifat Monopoli
Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Misalnya negara dapat mengatakan bahwa aliran kepercayaan atau partai politik tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara.
3. Sifat Mencakup Semua ( All - embracing )
Semua peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Hal itu perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.
BENTUK-BENTUK KENEGARAAN
Ada beberapa bentuk-bentuk kenegaraan, antara lain adalah :
Koloni
Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain . Dalam negara koloni,urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih tergantung pada negara yang menjajahnya.
Contoh : Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama lebih kurang 350 tahun.
Trustee ( Perwalian )
Trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang .
Contoh : Papua New Guinea bekas jajahan Inggris berada di bawah naungan PBB sampai
dengan tahun 1975.
Mandat
Mandat adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa - Bangsa ( LBB ).
Contoh : Negara Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat Perancis
Dominion
Dominion adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai raja/ratunya (lambang persatuan).
Negara-negara dominion tergabung dalam The British Commonwealth of Nations ( Negara-negara Persemakmuran ). Negara-negara dominion mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan penuh dalam mengurus praktek-praktek ke dalam maupun ke luar.
Contoh : Negara Kanada, Australia , Selandia Baru , dan Afrika Selatan .
Uni
Uni adalah gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama.
Uni dapat dibedakan tiga macam yaitu :
a). Uni Personil ( Personele Unie ) yaitu dua negara yang kebetulan mempunyai raja yang
sama sebagai kepala negara . Sementara itu, segala urusan dalam dan luar negeri diurus
oleh masing-masing negara.
Contoh : * Benelux ( Belgia , Nederland , dan Luxemburg ) yang tergabung dalam Uni
Personil tahun 1839 - 1890
* Inggris - Scotland tahun 1603 - 1707
b). Uni Riil ( Reele Unie ) yaitu dua negara yang berdasarkan suatu traktat mengadakan
ikatan yang dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat perlengkapan uni guna
mengatur kepentingan bersama . Kepentingan bersama itu umumnya berupa persoalan-
persoalan yang menyangkut politik luar negeri.
Contoh : * Uni Austria - Hongaria tahun 1867 - 1919
* Uni Swedia - Norwegia tahun 1815 - 1905
c). Uni Zui Generalis yaitu gabungan negara yang mempunyai alat kelengkapan bersama
untuk mengurus kepentingan hubungan luar negeri , setelah adanya kesepakatan lewat
perjanjian.
Contoh : Uni Indonesia - Belanda tahun 1949 - 1950
TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA
A. Tujuan Negara
Negara dapat dipandang sebagai persekutuan manusia yang hidup dan bekerjasama
untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Pada umumnya tujuan akhir setiap negara adalah
menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Oleh karena itu bagi suatu negara, tujuan merupakan hal yang sangat penting sebab tujuan
akan sangat menentukan bagaimana suatu negara mengatur, menyusun, dan menyelenggara-
kan pemerintahannya guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
Sejalan dengan banyaknya corak tujuan yang hendak diwujudkan oleh suatu negara,
banyak pemikir negara dan ahli hukum yang membahas dan mengemukakannya dalam
suatu teori. Beberapa di antaranya adalah :
Nama Tokoh
Tujuan Negara
a. Lord Shang Yang
Mencapai kekuasaan negara dengan cara rakyat dan negara harus berbanding terbalik. Bila negara ingin kuat dan sejahtera, maka rakyat harus lemah, miskin, dan bodoh.
b. Niccolo Machiavelli
Mencapai kekuasaan negara dengan cara menitik-beratkan pada sifat pribadi raja, agar dapat cerdik seperti kancil dan menakut-nakuti rakyatnya seperti singa .
c. Dante Alleghieri
Mencapai perdamaian dunia dengan cara membentuk satu negara di bawah satu imperium dunia ( raja atau kaisar ).
d. Immanuel Kant
Menjamin hak dan kebebasan warga negara .
e. Kranenburg
Mengupayakan kesejahteraan warga negaranya
(Welfare State)
Tujuan Negara Republik Indonesia terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
IV, yaitu :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial .
B. Fungsi Negara
Fungsi Negara perlu ditetapkan sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi
tercapainya tujuan Negara.
Tokoh-tokoh yang pendapatnya tentang fungsi negara diterapkan oleh negara-negara di
dunia adalah :
* John Locke
John Locke membedakan fungsi negara menjadi tiga yaitu :
1. Fungsi Legislatif : membuat Undang-Undang.
2. Fungsi Eksekutif : melaksanakan Undang-Undang , termasuk mengadili pelanggar
Undang - Undang.
3. Fungsi Federatif : mengurusi urusan luar negeri dan perang serta damai
( Hubungan dengan negara lain ).
* Montesquieu
Montesquieu membedakan fungsi negara atas tiga tugas pokok yaitu :
1. Fungsi Legislatif : membuat Undang-Undang.
2. Fungsi Eksekutif : melaksanakan Undang-Undang , termasuk mengadakan
hubungan luar negeri, membuat perjanjian dengan negara lain,
dll.
3. Fungsi Yudikatif : mengawasi agar semua peraturan ditaati ( fungsi mengadili
terhadap pelanggar Undang-Undang ).
PATRIOTISME DAN NASIONALISME
Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang sudi mengorbankan
segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.
Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri .
Nasionalisme menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Nasionalisme dalam arti sempit
Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya
yang sangat tinggi dan berlebihan, namun terhadap bangsa lain memandang rendah. Hal ini sering disamakan dengan Jingoisme atau Chauvinisme.
2. Nasionalisme dalam arti luas
Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan
bangsanya yang tinggi, tetapi terhadap bangsa lain tidak memandang rendah.
Kamis, 07 Agustus 2008
Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia
Halaman ini merupakan daftar suku bangsa yang hidup di Indonesia:
Klik link ini untuk lebih lanjut : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_suku_bangsa_di_Indonesia Read More...
Klik link ini untuk lebih lanjut : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_suku_bangsa_di_Indonesia Read More...
Minggu, 03 Agustus 2008
LINK INDONESIA
Lembaga-Lembaga Negara
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi-Komisi Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Yudisial
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Ombudsman
Departemen
Departemen Dalam Negeri
Departemen Luar Negeri
Departemen Pertahanan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Departemen Komunikasi dan Informatika
Departemen Keuangan
Departemen Perdagangan
Departemen Perindustrian
Departemen Perhubungan
Departemen Pekerjaan Umum
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Departemen Pertanian
Departemen Kehutanan
Departemen Kelautan dan Perikanan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Departemen Kesehatan
Departemen Pendidikan Nasional
Departemen Sosial
Departemen Agama
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian/Lembaga Setingkat Menteri
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Perekonomian
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Kementerian Negara Riset dan Teknologi/BPPT
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Kementerian Negara BUMN
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
Sekretariat Negara
Sekretariat Kabinet
Kejaksaan Agung
TNI dan POLRI
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Markas Besar Kepolisian Negara
Bank Indonesia
Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Departemen
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan Akuntansi Keuangan Negara
Badan Intelijen Negara
Badan Kepegawaian Negara
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Badan Meteorologi dan Geofisika
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Pertanahan Nasional
Badan Pusat Statistik
Badan Standarisasi Nasional
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Urusan Logistik
Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Informasi Nasional
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Badan Narkotika Nasional
Pemerintah-Pemerintah Propinsi:
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Propinsi Sumatera Utara
Propinsi Sumatera Barat
Propinsi Riau
Propinsi Kepulauan Riau
Propinsi Jambi
Propinsi Bengkulu
Propinsi Sumatera Selatan
Propinsi Bangka-Belitung
Propinsi Lampung
Propinsi Banten
Propinsi DKI Jakarta
Propinsi Jawa Barat
Propinsi Jawa Tengah
Propinsi D.I. Yogyakarta
Propinsi Jawa Timur
Propinsi Kalimantan Barat
Propinsi Kalimantan Tengah
Propinsi Kalimantan Selatan
Propinsi Kalimantan Timur
Propinsi Bali
Propinsi Nusa Tenggara Barat
Propinsi Nusa Tenggara Timur
Propinsi Sulawesi Selatan
Propinsi Sulawesi Barat
Propinsi Sulawesi Tenggara
Propinsi Sulawesi Tengah
Propinsi Gorontalo
Propinsi Sulawesi Utara
Propinsi Maluku
Propinsi Maluku Utara
Propinsi Irian Jaya Barat
Provinsi Papua Read More...
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi-Komisi Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Yudisial
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Ombudsman
Departemen
Departemen Dalam Negeri
Departemen Luar Negeri
Departemen Pertahanan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Departemen Komunikasi dan Informatika
Departemen Keuangan
Departemen Perdagangan
Departemen Perindustrian
Departemen Perhubungan
Departemen Pekerjaan Umum
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Departemen Pertanian
Departemen Kehutanan
Departemen Kelautan dan Perikanan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Departemen Kesehatan
Departemen Pendidikan Nasional
Departemen Sosial
Departemen Agama
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian/Lembaga Setingkat Menteri
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Perekonomian
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Kementerian Negara Riset dan Teknologi/BPPT
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Kementerian Negara BUMN
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
Sekretariat Negara
Sekretariat Kabinet
Kejaksaan Agung
TNI dan POLRI
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Markas Besar Kepolisian Negara
Bank Indonesia
Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-Departemen
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan Akuntansi Keuangan Negara
Badan Intelijen Negara
Badan Kepegawaian Negara
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Badan Meteorologi dan Geofisika
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Pertanahan Nasional
Badan Pusat Statistik
Badan Standarisasi Nasional
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Urusan Logistik
Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Informasi Nasional
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Badan Narkotika Nasional
Pemerintah-Pemerintah Propinsi:
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Propinsi Sumatera Utara
Propinsi Sumatera Barat
Propinsi Riau
Propinsi Kepulauan Riau
Propinsi Jambi
Propinsi Bengkulu
Propinsi Sumatera Selatan
Propinsi Bangka-Belitung
Propinsi Lampung
Propinsi Banten
Propinsi DKI Jakarta
Propinsi Jawa Barat
Propinsi Jawa Tengah
Propinsi D.I. Yogyakarta
Propinsi Jawa Timur
Propinsi Kalimantan Barat
Propinsi Kalimantan Tengah
Propinsi Kalimantan Selatan
Propinsi Kalimantan Timur
Propinsi Bali
Propinsi Nusa Tenggara Barat
Propinsi Nusa Tenggara Timur
Propinsi Sulawesi Selatan
Propinsi Sulawesi Barat
Propinsi Sulawesi Tenggara
Propinsi Sulawesi Tengah
Propinsi Gorontalo
Propinsi Sulawesi Utara
Propinsi Maluku
Propinsi Maluku Utara
Propinsi Irian Jaya Barat
Provinsi Papua Read More...
Langganan:
Postingan (Atom)